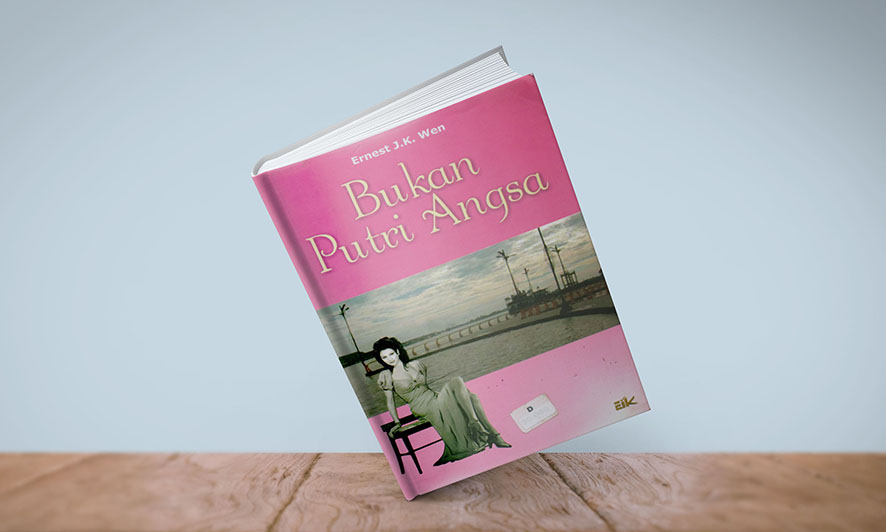
Febi tidak terlihat seperti keturunan keluarga Yap yang rata-rata berwajah persegi. Seperti lukisan Kubilai Khan, si penakluk dari Mongolia itu. Febi memiliki kecantikan yang sangat sempurna, seakan dia terbentuk dari bagian-baian gen terbaik ayah-ibunya. Wajahnya yang lonjong adalah arisan ibunya, hidungnya yang mancung adalah turunan dari ayahnya. Sedangkan bibirnya yang sensual adalah karunia tambahan (hal 9).
Kalau saja tidak diawali dengan bab kecil “Naomi” (hal 7), kemungkinan besar bisa terjebak kepada siapa tokoh utama yang diperankan dalam novel ini. Penggambaran sosok Febi yang demikian sempurna bisa menggiring pada simpulan bahwa peran utamanya adalah “Putri Angsa” itu. Padahal, sesuai dengan judul novel ini, Ernest mencoba memunculkan sosok Naomi yang berupaya membalas dendam kepada Yap Fuk-Shen. Tentu saja, dia “Bukan Putri Angsa”.
Naomi yang merupakan “anak haram” dari perselingkuhan ibunya dengan Yap ini digambarkan sebagai pegawai sebuah perusahaan besar, kalau tidak disebut raksasa, milik Yap di Pontianak. “Yap Fuk-shen itu? Hm, dia bukan saja bosku, tapi ayahku!” (hal 197) Dendam sejarah itulah yang kemudian mendorong Naomi untuk melakukan apa saja agar dendamnya terbalaskan. Dia akhirnya menyusup menjadi pegawai di PT Japindo sebagai Manajer Keuangan.
Bila dicermati, perjalanan Naomi untuk menuntaskan dendam ini sebenarnya tidak terlalu menarik. Alur cerita yang dibuat Ernest relatif datar, jarang ditemukan adanya kejutan. Malah, kisah cinta antara Febi dan Herman lah yang boleh dibilang lebih menyentuh. Bagaimana perjuangan seorang keturunan taoke untuk menjalin asmara dengan dokter muda yang keturunan Tionghoa kere sekaligus musuh bisnis ayahnya. Pertemuan keduanya di atas kapal barang juga cukup menarik (hal 25-36).
Nah, hal yang lebih menarik tentu saja adalah teknik pengungkapan masalah yang digunakan Ernest tentang mafia pajak dan likuiditas perbankan di kalangan pengusaha Tionghoa dengan pejabat pemerintah. Ernest berupaya “menelanjangi” praktik korupsi, kolusi, penggelapan pajak, penyalahgunaan HPH, hingga money laundry. Ungkapan-ungkapan yang lugas mengenai suap dan sogok seakan membuka mata pembaca untuk melihat kebobrokan rezim Orde Baru (hal 264-268).
Dengan mengambil setting cerita sekitar 1997 hingga awal dekade pertama abad 21, Ernest mengungkapkan bagaimana perubahan iklim bisnis di Indonesia. Termasuk di dalamnya tentang olengnya pengusaha keturunan setelah kejatuhan penguasa Orde Baru. Menariknya lagi, penulis menggunakan nyaris 100 persen tokoh-tokoh warga keturunan Tionghoa sebagai pemeran ceritanya. Ini bisa dimengerti mengingat perbandingan penduduk keturunan dengan pribumi di Pontianak mencapai 50:50.
Konstruksi wacana yang dikedepankan Ernest seakan ingin menghindari dimensi moral yang sangat personal. Pembaca tidak akan menemukan sentuhan moral dalam novel ini. Sebaliknya, gambaran cinta yang lebih sarat dalam bingkai biologis sekaligus psikologis lebih mengemuka. Lihat saja misalnya saat pasangan dokter muda bertukar kondom (hal 245) atau seorang suami memaklumi istrinya bermain gila dengan majikan di perusahaannya (hal 227-228).
Lebih besar dari itu, Ernest ingin mengungkapkan wacana besar tentang pentingnya akuntabilitas publik dalam pengelola perusahaan maupun pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Naomi memang berhasil. Tapi sekali lagi, dia “Bukan Putri Angsa”. Cuma saja, pembaca yang jeli menyelami sosok Naomi bisa saja berkesimpulan bahwa dia juga tengah memainkan peran ganda, yakni merebut kekuasaan perusahaan.(Najip HS Parino)
